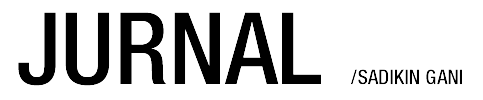Kisah Desa Dirundung Pilu
Seorang kawan baru pulang dari desanya di Jawa Timur. Liburan lebaran tempo hari. Dia berkisah bahwa tetangganya di desa banyak yang berusaha keras menabung demi bisa pergi naik haji.
Mereka bukan orang-orang mampu secara ekonomi. Serba kekurangan. Rumah mereka bahkan ada yang sudah miring mau ambruk. Tapi tetap memaksakan diri mengurangi kebutuhan pokoknya demi memenuhi tabungan pergi naik haji. Kurang lebih begitu sang kawan berkisah.
“Dan jangan salah, pak Iknay (demikian dia memanggil saya), sales tabungan haji itu sangat aktif memengaruhi orang desa. Didukung pemuka-pemuka agama setempat,” katanya.
Ini kisah baru bagi saya. Selama mondar-mandir ke desa Jawa belum menemukan fenomena seperti itu. Sepengetahuan saya, sekitar enam tahun ke belakang, institusi ekonomi lokal yang banyak berkembang di pedesaan Jawa adalah arisan.
Arisan di desa macam-macam. Kita bisa menemukan arisan atas perbedaan jender. Arisan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada pula arisan bapak-bapak pengajian dan ibu-ibu pengajian. Ada yang hanya lingkup rukun tetangga (RT), ada pula lingkup rukun warga (RW).
Arisan lain yang berkembang adalah arisan semen dan batu-bata. Materi yang diarisankannya adalah gabah hasil panen yang dikonversi ke nominal uang.
Di desa Kalijirek, Kebumen, Jawa Tengah, seorang petani berstatus pemilik dan penggarap dengan tangkas menunjukkan kepada saya setiap bagian rumahnya yang dibangun dari hasil arisan. Pondasi rumah, dinding, hingga atapnya. Hal serupa dialami hampir setiap petani dan buruh tani di desa itu.
Seorang buruh tani mengajak saya ke pelataran samping rumahnya. Dia menunjukkan bahwa tumpukan batu-bata yang ditutupi terpal adalah hasil arisan beberapa musim panen lalu. Belum bisa dipakai karena masih menunggu hasil arisan semen di musim panen berikutnya.
Petani yang mengalokasikan gabah hasil panen untuk arisan kebutuhan papan bukan berarti dia memiliki surplus bersih hasil panen. Gabah-gabah arisan itu adalah hasil pemotongan dari alokasi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Agar bisa ikut arisan, maka harus menyediakan sekian banyak gabah hasil panen. Agar itu terpenuhi, maka kebutuhan lain harus ditekan. Istilah sesatnya “berhemat”. Substansinya, menekan tingkat kebutuhan yang satu untuk memenuhi kebutuhan lain yang dianggap prioritas. Sayangnya, itu terjadi bukan menekan kebutuhan sekunder atau lux demi memenuhi kebutuhan primer; melainkan menekan tingkat kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan primer lainnya.
“Kalo ndak arisan ya ndak bisa bangun rumah tembok, mas,” katanya.
“Cuma haji ‘Takur’ yang bisa bangun rumah gak ikut arisan,” sambung pemuda yang biasa mengantar saya keliling desa.
Tuan Takur adalah istilah untuk pemilik tanah luas di desa Kalijirek. Istilah itu diambil dari nama seorang tuan tanah di film India. Istilahnya sendiri lebih banyak digunakan oleh kalangan muda.
Menyaksikan kenyataan bagaimana orang Desa Kalijirek membangun rumah, cacat sudah salah satu parameter tingkat kesejahteraan yang mendasarkan pada pemilikan jenis bangunan rumah (permanen, semi permanen). Dan kesimpulan ahistoris cacatnya permanen. Tragisnya, kesimpulan-kesimpulan semacam itu yang (seringkali, atau bahkan selalu?) dijadikan pijakan penyelenggara negara dalam membuat perencanaan pembangunan. Kesimpulan-kesimpulan cacat itu pulalah yang kerap dijadikan pembelaan politik partai berkuasa kala digugat tanggungjawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan mayoritas warga negara Indonesia.